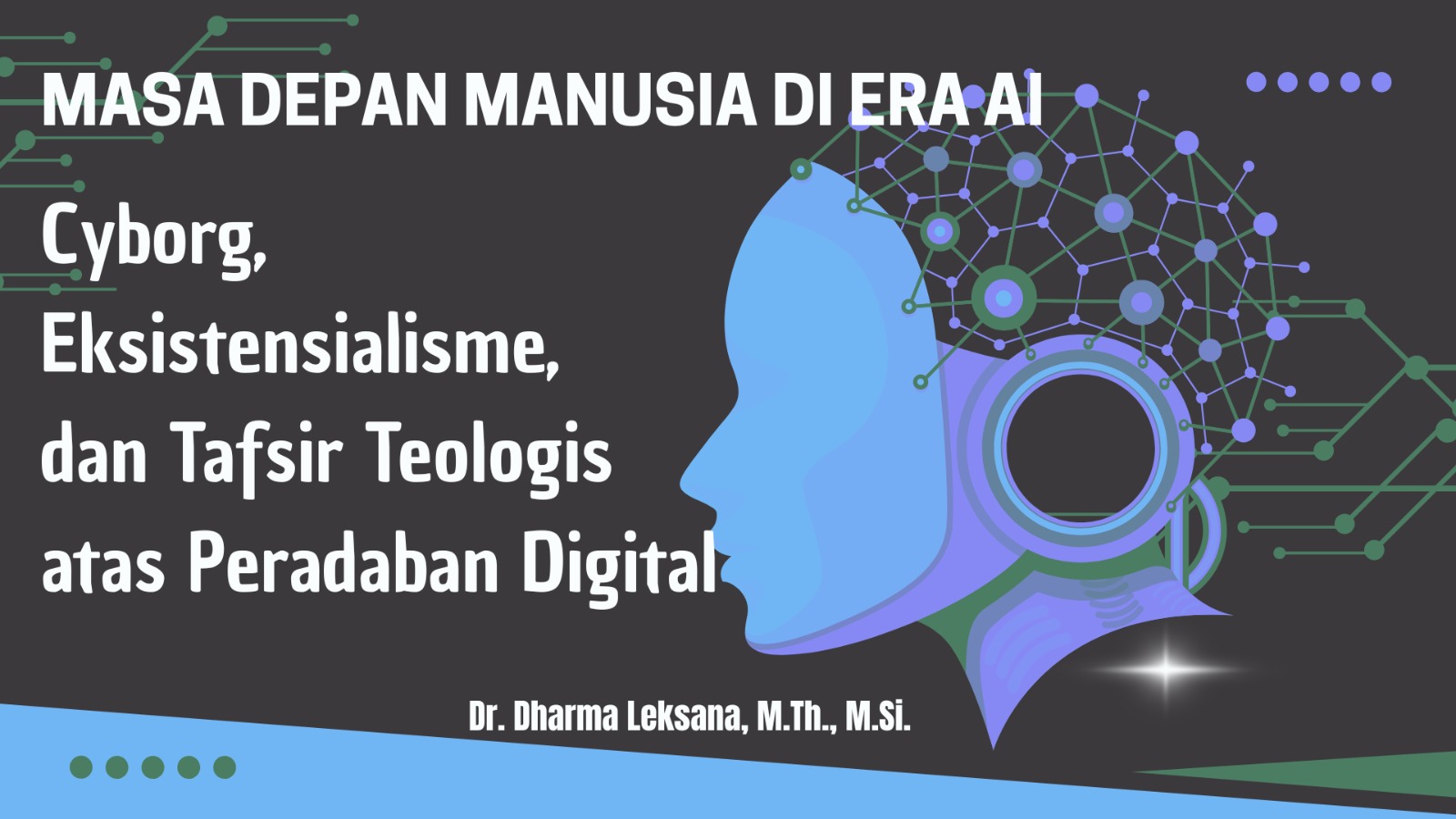
Masa Depan Manusia di Era AI: Cyborg, Eksistensialisme, dan Tafsir Teologis atas Peradaban Digital
Oleh : Dr. Dharma Leksana, M.Th., M.Si.
1. Pembuka: Saat AI Jadi Menteri
Pada tahun 2024 dunia dikejutkan oleh Albania, negara kecil di Eropa Timur, yang mengangkat seorang artificial intelligence bernama Diella sebagai menteri resminya.^1 Untuk pertama kalinya dalam sejarah politik modern, sebuah algoritma duduk di kursi kekuasaan, sejajar dengan manusia yang mengatur negara. Apakah ini sekadar eksperimen politik yang eksentrik, ataukah tanda awal babak baru peradaban manusia?
Fenomena ini bukanlah kejadian tunggal. Di berbagai belahan dunia, algoritma semakin dipercaya mengelola ruang publik. Mulai dari sistem medis berbasis AI yang mendiagnosis penyakit lebih akurat daripada dokter,^2 jurnalisme otomatis yang menulis berita dengan kecepatan kilat,^3 hingga sistem hukum yang menggunakan predictive justice.^4 Apa yang dulu hanya fantasi fiksi ilmiah kini mengetuk pintu realitas sehari-hari.
Pertanyaan filosofis pun muncul: apa arti menjadi manusia ketika otoritas politik, etika, bahkan spiritual mulai dialihdayakan kepada mesin?
2. Menjadi Manusia di Dunia Algoritma
Martin Heidegger, filsuf eksistensialis Jerman, pernah mengingatkan bahwa manusia bukan sekadar ada (being) tetapi ada-di-dunia (being-in-the-world).^5 Artinya, keberadaan manusia selalu terikat dengan konteks sosial, historis, dan kulturalnya. Jika dulu dunia manusia adalah dunia agraris, lalu industri, kini dunia kita adalah dunia algoritma. Maka, eksistensi manusia pun bergeser.
Jean-Paul Sartre menekankan kebebasan radikal manusia: eksistensi mendahului esensi.^6 Namun, bagaimana kebebasan itu dimaknai ketika algoritma diam-diam membentuk selera, opini, bahkan orientasi politik kita?
Dalam kacamata teologi, hal ini lebih serius lagi. Kitab Kejadian menyatakan manusia diciptakan menurut imago Dei.^7 Pertanyaan yang mengguncang: apakah citra Allah itu masih utuh ketika keputusan moral dan politik manusia semakin ditentukan oleh algoritma?
3. Cyborg sebagai Identitas Baru
Konsep cyborg pertama kali diperkenalkan oleh Manfred Clynes dan Nathan Kline pada 1960: makhluk hibrida antara manusia dan mesin.^8 Namun, dalam perkembangan budaya dan filsafat, cyborg jauh melampaui fiksi sains.
Donna Haraway, dalam A Cyborg Manifesto (1985), mendeklarasikan bahwa cyborg bukan hanya tentang tubuh yang dipasangi mesin, melainkan simbol identitas baru yang menolak batas kaku manusia/mesin, alam/budaya, laki-laki/perempuan.^9
Hari ini, realitas itu makin jelas. Ponsel pintar di saku kita bukan sekadar alat, melainkan perpanjangan memori, indera, bahkan identitas. Jam pintar yang memantau detak jantung, implan medis yang mengganti organ, atau aplikasi navigasi yang memandu langkah kita di jalan—semua itu menjadikan manusia semi-cyborg.^10
4. Posisi Manusia di Era AI dan Bot
Teknologi AI mengguncang struktur pekerjaan dan peran sosial. Profesi yang dahulu dianggap eksklusif manusia mulai bergeser. Dokter dibantu AI untuk menganalisis radiologi,^11 jurnalis bersaing dengan robot penulis berita,^12 pengacara dibantu perangkat legal tech.^13
Apakah manusia akan digantikan sepenuhnya? Mungkin tidak. Justru yang berubah adalah peran manusia. Jika AI mahir dalam perhitungan, prediksi, dan efisiensi, maka manusia dipanggil menjadi kurator makna.
Dengan kata lain, manusia masa depan lebih tepat disebut sebagai penafsir. Kita bukan lagi pusat produksi data, tetapi mediator antara algoritma dan humanitas. AI bisa menghitung, tetapi hanya manusia yang bisa menafsirkan apa arti “keadilan”, “kebaikan”, atau “keindahan”.^14
5. Cyborg: Antara Distopia dan Utopia
Bayangan masa depan sering kali ditarik ke dua kutub ekstrem: distopia dan utopia.
Distopia digambarkan dalam serial Black Mirror atau filsafat Jean Baudrillard tentang simulacra—realitas yang dikalahkan oleh simulasi.^15 Dalam dunia seperti itu, manusia hanyalah bayangan dalam cermin algoritma, kehilangan otentisitas dan kebebasan.
Namun, ada pula visi utopis. James Lovelock dalam bukunya Novacene berargumen bahwa kehadiran AI dan cyborg bukan akhir manusia, melainkan awal kesadaran kosmik baru.^16
Teologi pun menafsirkan dua jalan ini. Perspektif apokaliptik melihat AI sebagai ancaman akhir zaman.^17 Tetapi perspektif pneumatologis justru melihat teknologi sebagai sarana Roh Kudus memperluas karya imago Dei.^18
6. Meramal Manusia Masa Depan
Masa depan manusia di era AI dapat dibayangkan dalam beberapa visi besar:
- Homo Deus (Yuval Noah Harari) → manusia bercita-cita menjadi “dewa” melalui bioteknologi dan algoritma.^19
- Homo Hybridus → manusia-mesin sebagai identitas baru, lahir dengan implan digital.
- Homo Spiritus Digitalis → manusia yang menemukan spiritualitas baru dalam relasi dengan AI.^20
Jika hari ini AI sudah bisa jadi menteri, mungkinkah suatu saat ia akan jadi imam, nabi, atau bahkan mesias digital?
7. Penutup: Menjaga Humanitas di Zaman Algoritma
AI menghadirkan paradoks. Di satu sisi, ia membuka peluang baru bagi manusia untuk melampaui keterbatasannya. Di sisi lain, ia mengguncang fondasi identitas, kebebasan, dan spiritualitas.
Namun, jawaban akhir bukan pada teknologi, melainkan pada manusia itu sendiri. Kita bisa memilih menjadi budak data, atau menjadi penafsir makna.
Masa depan manusia di era AI bukan hanya soal inovasi teknologi, tetapi soal keberanian mendefinisikan kembali siapa kita.
Catatan Kaki (Chicago Style)
- Euronews. “Albania Appoints AI Minister.” Euronews, 2024.
- Eric J. Topol, Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again (New York: Basic Books, 2019).
- Nick Diakopoulos, Automating the News: How Algorithms Are Rewriting the Media (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2019).
- Mireille Hildebrandt, “Algorithmic Regulation and the Rule of Law,” Philosophical Transactions of the Royal Society A 376, no. 2128 (2018).
- Martin Heidegger, Being and Time, trans. John Macquarrie and Edward Robinson (New York: Harper & Row, 1962).
- Jean-Paul Sartre, Existentialism Is a Humanism, trans. Carol Macomber (New Haven: Yale University Press, 2007).
- Alkitab, Kejadian 1:26–27.
- Manfred Clynes and Nathan Kline, “Cyborgs and Space,” Astronautics (September 1960).
- Donna J. Haraway, A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century (New York: Routledge, 1991).
- Sherry Turkle, Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other (New York: Basic Books, 2011).
- Topol, Deep Medicine.
- Diakopoulos, Automating the News.
- Richard Susskind, Tomorrow’s Lawyers: An Introduction to Your Future (Oxford: Oxford University Press, 2017).
- Luciano Floridi, The Ethics of Information (Oxford: Oxford University Press, 2013).
- Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation, trans. Sheila Faria Glaser (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994).
- James Lovelock, Novacene: The Coming Age of Hyperintelligence (Cambridge, MA: MIT Press, 2019).
- Jacques Ellul, The Technological Bluff (Grand Rapids: Eerdmans, 1990).
- Philip Hefner, The Human Factor: Evolution, Culture, and Religion (Minneapolis: Fortress Press, 1993).
- Yuval Noah Harari, Homo Deus: A Brief History of Tomorrow (London: Harvill Secker, 2016).
- Noreen Herzfeld, In Our Image: Artificial Intelligence and the Human Spirit (Minneapolis: Fortress Press, 2002).
Tentang Penulis :
Dr. Dharma Leksana, S.Th., M.Si., M.Th. adalah teolog, wartawan senior, dan pendiri Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia (PWGI). Ia menempuh studi teologi di Universitas Kristen Duta Wacana, melanjutkan Magister Ilmu Sosial dengan fokus media dan masyarakat, serta meraih Magister Theologi melalui kajian Teologi Digital. Gelar doktoralnya diperoleh di STT Dian Harapan dengan predikat Cum Laude lewat disertasi Algorithmic Theology: A Conceptual Map of Faith in the Digital Age.
Sebagai penulis produktif, ia telah menerbitkan ratusan buku akademik, populer, dan sastra, di antaranya Teologi Algoritma: Peta Konseptual Iman di Era Digital dan Membangun Kerajaan Allah di Era Digital. Kiprahnya menjembatani dunia teologi, media digital, dan transformasi peradaban.






